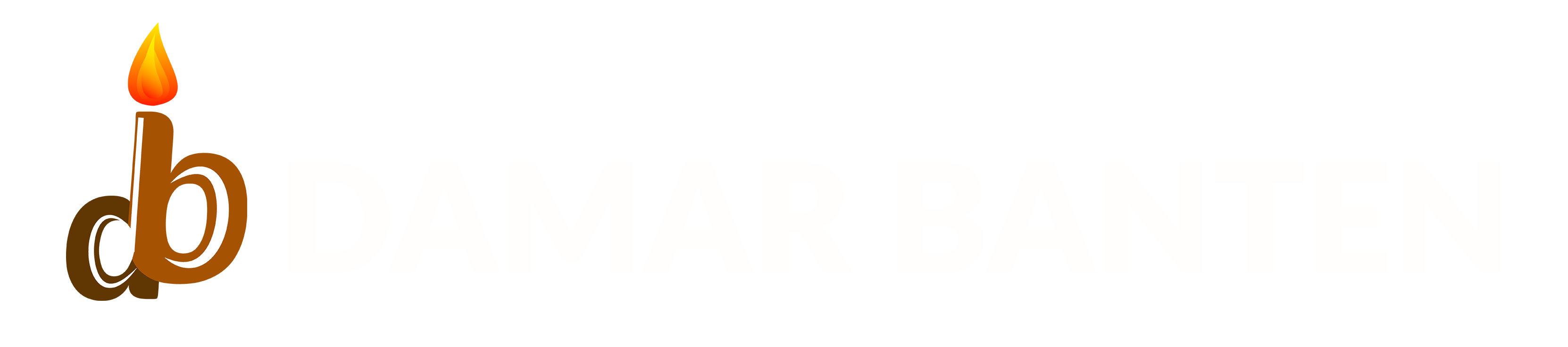Oleh: Zen L, M.Pd
Departemen ESDM PP AMPG
Media sosial kini telah menjadi ruang baru bagi publik untuk menyalurkan pandangan, kritik, dan ekspresi terhadap kebijakan negara. Dalam konteks demokrasi, ini seharusnya menjadi hal yang positif dan tanda bahwa masyarakat semakin berani berbicara dan berpartisipasi. Namun, ruang digital yang seharusnya menjadi wadah pertukaran ide justru sering berubah menjadi arena perundungan. Fenomena body shaming terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi contoh nyata betapa rendahnya etika diskusi kita di dunia maya.
Sebagai pejabat negara, Menteri ESDM memegang tanggung jawab besar terhadap sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat: harga BBM, pengelolaan tambang, transisi energi, hingga kebijakan energi baru terbarukan. Setiap kebijakan yang ia ambil tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, ketika kritik berubah menjadi serangan terhadap fisik, gaya bicara, atau latar belakang pribadi, maka diskursus publik telah bergeser dari ranah intelektual ke ranah emosional yang destruktif.
Fenomena ini menandakan rendahnya literasi digital dan empati sosial di masyarakat. Banyak warganet yang belum memahami bahwa media sosial bukan ruang bebas nilai. Setiap kalimat yang diunggah memiliki konsekuensi moral dan sosial. Body shaming, meskipun sering dianggap “candaan”, sejatinya merupakan bentuk kekerasan verbal yang bisa melukai martabat manusia. Ironisnya, sebagian pelaku tidak merasa bersalah mereka merasa sedang mengekspresikan pendapat, padahal yang dilakukan adalah penghinaan.

Padahal, performa dan kapasitas seorang pejabat tidak diukur dari bentuk tubuh, warna kulit, atau gaya berbicara. Seorang Menteri ESDM dinilai dari bagaimana ia menyusun kebijakan, mengelola sumber daya, dan menjaga kepentingan nasional. Namun di ruang digital yang serba cepat dan sensasional, perdebatan substansial sering kalah oleh komentar-komentar dangkal yang lebih menarik perhatian algoritma. Inilah tantangan besar demokrasi digital kita: substansi kalah oleh sensasi.
Krisis etika digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kualitas demokrasi. Ketika publik lebih fokus menghina daripada mengkritik secara rasional, maka pejabat publik akan sulit mendapat masukan yang objektif. Padahal, esensi demokrasi adalah check and balance, saling mengoreksi dengan cara yang beradab. Jika kritik berubah menjadi cercaan, maka yang tumbuh bukanlah demokrasi yang sehat, melainkan budaya kebencian.
Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan paradoks sosial di Indonesia. Di satu sisi, kita dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun dan nilai kemanusiaan. Namun di sisi lain, di dunia digital kita bisa dengan mudah melontarkan kata-kata kasar kepada orang yang bahkan tidak kita kenal secara pribadi. Dunia maya seakan membuat banyak orang lupa bahwa di balik akun pejabat, ada manusia dengan keluarga dan perasaan yang bisa terluka.
Sudah saatnya kita menyadari bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan menghina. Ruang digital seharusnya menjadi tempat berdiskusi, bukan berkelahi. Kritik harus berbasis data dan argumen, bukan emosi atau kebencian pribadi. Jika masyarakat ingin pejabat publik berubah, maka cara menyampaikan kritik pun harus bermartabat. Kata-kata yang sopan justru lebih kuat dalam menggerakkan perubahan daripada hinaan yang melukai.
Kasus body shaming terhadap Menteri ESDM ini menjadi cermin bagi kita semua. Ia bukan sekadar persoalan individu, tetapi gejala sosial dari budaya komunikasi yang mulai kehilangan arah. Kita perlu membangun literasi digital yang tidak hanya teknis seperti cara menggunakan media sosial tetapi juga etis dan empatik. Pemerintah, media, dan masyarakat sipil harus bekerja sama membangun budaya digital yang sehat, di mana perbedaan pendapat dihormati, bukan dicaci.
Demokrasi yang matang tidak diukur dari seberapa keras kita berteriak di media sosial, tetapi seberapa santun kita bisa berbeda pendapat. Jika bangsa ini ingin maju, maka diskursus publiknya pun harus naik kelas, dari caci maki menjadi dialog, dari body shaming menjadi argumentasi.