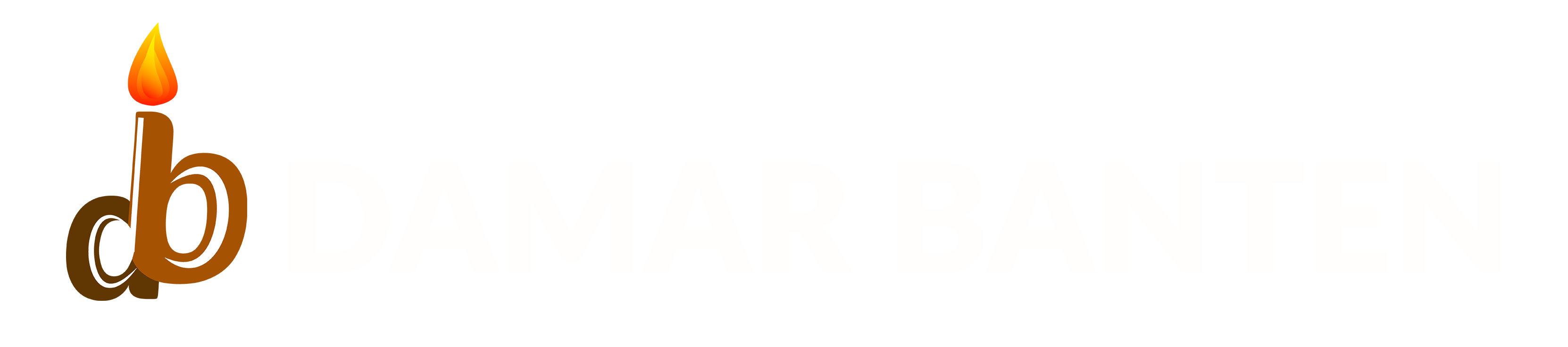Damar Banten – Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dilakukan sebuah usaha-usaha guna menyebar luaskan berita mengenai kemerdekaan tersebut ke setiap daerah-daerah. Di Banten sendiri, kabar tersebut memunculkan reaksi yang berbeda-beda pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya merupakan kelompok jawara yang menganggap jika kemerdekaan diartikan sebagai sebuah proses pembersihan Banten secara tuntas, atas sisa-sisa kolonial serta unsur-unsur yang masih berkaitan dengan kolonial.
Akan tetapi, cara-cara yang dilakukan atas respon tersebut mengarah pada berbagai tindakan kekerasan semisal penculikan, pendaulatan, provokasi, intimidasi, perampokan, bahkan pembunuhan. Hal tersebut banyak menyebabkan keresahan pada kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan pemerintah, yang melihat jika tindakan itu sudah mengarah kepada tindakan pemberontakan, yang menginginkan penggulingan atas kekuasaan yang sah, serta menggantinya dengan pemerintahan yang diinginkan.
Pemberontakan atas Jawara Banten di masa awal kemerdekaan, tercerminkan atas terjadinya beberapa peristiwa yang di antaranya merupakan peristiwa Cinangka, penyerangan markas kampetai, serta aksi Dewan Rakyat. Peristiwa Cinangka terjadi akibat situasi Banten yang pada saat itu semakin memburuk secara mencolok di tahun 1945. Kekurangan atas sandang pangan di kalangan masyarakat terutama para petani, yang menjadi mayoritas penduduk yang nampaknya semakin parah dan menjad-jadi. Tanda pertama atas peristiwa tersebut ialah terjadinya ketegangan sosial di antara para petani atas para Pangreh Praja. Ketegangan tersebut memungkinkan untuk menjadi sebuah kekacauan yang meluas kemana-mana pada Agustus 1945. Ketika itu, di kawedanaan Anyer sedang terjadi berbagai kerusuhan yang memungkinkan bisa menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Di 16 Agustus 1945, para petani Cinangka mendatangi rumah camat setempat, yaitu Tubagus Muhammad Arsyad, guna meminta supaya bahan sandang yang dikuasainya diserahkan kepada mereka. Ketika camat tersebut menolak permintaan itu, pada akhirnya rumah beserta isinya segera dirampok. Alhasil, dirinya kemudian kabur menuju Anyer guna meminta bantua kepada wedana.
Wedana Anyer pada saat itu dijabat oleh Raden Sukrawardi, kemudian pergi ke Cinangka diantar oleh camat serta dua orang polisi, guna menenangkan masyarakat serta mengajak mereka untuk berunding. Sayangnya, begitu rombongan tersebut masuk ke desa, tanpa pikir panjang sebuah serangan segera diluncurkan oleh para penduduk yang bersenjatakan tongkat. Pada peristiwa tersebut, Raden Sukrawardi akhirnya terbunuh sementara yang lainnya dapat berhasil kabur.
Pada 18 Agustus 1945, ketika 30 orang polisi beserta serdadu Jepang memasuki desa tersebut, mereka kemudian diserang sehingga terjadilah sebuah perkelahian secara massal, yang mengakibatkan seorang polisi serta 7 orang petani tewas. Dengan begitu, peristiwa tersebut dianggap sebagai pembuka jalan serta menjadi awal atas setiap rangkaian pemberontakan-pemberontakan, yang terjadi di Banten pada awal kemerdekaan. Peristiwa itu menyebabkan kekhawatiran pada pihak Jepang serta para pejabat Pangreh Praja setempat, yang saat itu menjadi sasaran utama pada setiap kerusuhan.
Pada peristiwa selanjutnya, merupakan sebuah penyerangan atas markas kampetai. Pada penyerangan tersebut, berbagai elemen masyarakat Banten terlibat secara bersama-sama, sekalipun pada saat itu mereka memiliki kelompok masing-masing. Beberapa kelompok yang terlibat kala itu didominasi oleh para barisan pemuda serta kelompok yang menamai dirinya sebagai laskar rakyat, yang terdiri atas para jawara. Para jawara yang tergabung ke dalam kelompok laskar tersebut ikut serta melakukan penyerangan terhadap markas kampetai, yang pada saat itu sebagai satu-satunya pertahanan terakhir Jepang di Banten. Penyerahan terhadap markas kampetai diawali dengan aksi penurunan bendera Jepang di berbagai instansi pemerintah, yang ada di Banten khususnya kota Serang sebagai pusat pemerintahan, sebagai tanda penyerahan kekuasaan atas Jepang terhadap rakyat.
Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak keresahan pada kalangan pejabat sipil Jepang, serta para pegawai Pangreh Praja, sehingga membuat mereka bergegas untuk segera meninggalkan Banten menuju Jakarta. Alhasil, Jabatan residen berpindah dari Yuki Yoshii diserahkan kepada Raden Tirtasujatna. Akan tetapi, Raden Tirtasujatna sendiri pada akhirnya juga meninggalkan Banten, akibat ada sebuah desas desus di kalangan masyarakat jika akan ada pembunuhan aparat pemerintah, yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang, akibat hal tersebut jabatan residen akhirnya menjadi kosong.
Pada akhirnya, rakyat kemudian berinisiatif untuk mengangkat K.H. Akhmad Khatib sebagai residen Banten pada 19 September 1945, dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Banten. Tokoh K.H. Akhmad Khatib merupakan seorang ulama yang cukup disegani masyarakat. Dirinya merupakan alumni pesantren Kadupiring, yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke pesantren Caringin, yang keduanya berada di Pandeglang. Bagi masyarakat Banten, K.H Akhmad Khatib merupakan seorang pimpinan yang paling diharapkan kelak di kemudian hari, dapat menggantikan kedudukan kesultanan Banten, karena dirinya merupakan keturunan terakhir dari kesultanan Banten yang berhak mewarisi
tahta kesultanan.
Rakyat Banten kala itu melakukan perundingan dengan pihak kampetai, supaya menyerahkan kekuasaan serta senjatanya ke pihak pemerintah. Hal tersebut kemudian disetujui dengan catatan jika proses evakuasi orang-orang Jepang yang berada di Banten, sudah berkumpul di Serang tanpa gangguan. Akan tetapi, suatu insiden terjadi yang mengakibatkan Jepang membatalkan perjanjian tersebut. Insiden itu merupakan pengutusan dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang mengutus Abdul Mukti serta Juhdi agar melakukan penjemputan pasukan angkatan darat Jepang (kaigun), di Sajira-Rangkasbitung, mereka dikawal 9 orang tentara Jepang. Sialnya, ketika di perjalanan mereka dihadang oleh rakyat tepat pada lintasan jalan kereta api di Warunggunung.
Akibat dibatalkannya perjanjian tersebut, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali melakukan penyerangan. Para pemimpin pasukan dari berbagai daerah seperti Ciomas, Pabuaran, Baros, Taktakan, Padarincang, Karamatwatu, Cilegon, serta Ciruas, datang menuju Kota serang guna membicarakan rencana rinci untuk melakukan penyerangan. Pada peristiwa penyerangan di markas kampetai tersebut, ada peran besar dari para jawara yang ikut serta melakukan aksi. Hal demikian dapat dilihat dari keberanian serta kenekatan aksi yang mereka lakukan. Itu dibuktikan dengan luapan kemarahan yang tidak terkendali, bahkan oleh para kelompok pasukannya itu sendiri, serta para pimpinan yang terlibat langsung seperti Salim Nonong, Soelaiman Gunungsari, serta Jaro Kamid.
Teriakan takbir bergema setelah penyerahan itu, hal tersebut merupakan suatu ungkapan untuk mengagungkan kebesaran Allah, dengan senantiasa mengharap ridho serta perlindungannya pada perang jihad melawan orang-orang yang dianggap kafir. Ketika situasi tersebut, terjadi sebuah konflik internal ketika K.H. Akhmad Khatib mulai mengumumkan susunan atas aparatur pemerintahan di seluruh wilayah Banten. K.H. Akhmad Khatib tetap kukuh mempertahankan para bupati di tiga kabupaten, yakni Serang, Pandeglang, serta Lebak. Alasan mepertahankan tiga kabupaten tersebut didasarkan pada para pegawai masih memiliki kemampuan dan tenaga, untuk dipakai serta dianggap memiliki kecakapan dalam menjalankan pemerintahan.
Susunan aparatur tersebut ternyata menyebabkan ketidakpuasan dari sebagian kalangan rakyat Banten, terlebih di kalangan para pemimpin jawara. Mereka berpendirian jika pada penyusunan pemerintahan di Banten perlu dihapuskan dari segala unsur kolonial, karena mereka merupakan para pengkhianat bahkan wajib dilenyapkan. Kelompok jawara tersebut adalah pimpinan dari Ce Mamat, seorang jawara yang pernah dibuang ke Boven Digul, karena terlibat pemberontakan PKI pada 1926. Atas ketidakpuasan tersebut, Ce Mamat kemudian berusaha untuk menghimpun basis kekuatan guna menggulingkan pemerintahan K.H. Achmad Khotib dengan membentuk Dewan Rakyat.
Kendati demikian, kedudukan atas K.H. Akhmad Khatib sebagai pemimpin Banten akan tetap dipertahankan, selain karena kharismanya di tengah-tengah masyarakat, juga memungkinkan terjadi pergolakan yang lebih besar jika K.H. Akhmad Khatib diganti. Pada akhirnya, yang akan diturunkan merupakan para Pangreh Praja yang merupakan orang-orang lama, yang berkuasa ketika masa kolonial Belanda dan Jepang. Ternyata keberadaan atas Dewan Rakyat tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena mereka harus kepada siapa menuruti perintah.
Pada akhirnya, terjadi dualisme kepemimpinan di Banten kala itu, di satu pihak ada residen, tetapi pada sisi lain ada Dewan Rakyat yang lebih mendominasi pemerintahan. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat akibat keberadaan dari pasukan Dewan Rakyat, yang ternyata membuat masyarakat ketakutan karena berbagai aksi perampokan serta perampasan terhadap penduduk. Terlihat jika gerakan atas Dewan Rakyat tersebut sebenarnya merupakan gerakan dari kelompok jawara, yang mulai terpolarisasi menjadi dua kekuatan. Hal tersebut tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para pimpinan jawara atas situasi politik yang berkembang pada massa itu.
Di awal bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, terjadi persaingan antara kelompok Soekarno dengan kelompok Tan Malaka, yang kemudian berimbas pada daerah-daerah termasuk Banten. Keberpihakan jawara selama ini terhadap rakyat pada akhirnya mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta ambisi tertentu, agar dapat berkuasa di Banten.
Gerakan dari Dewan Rakyat kemudian dapat ditumpas dengan tertangkapnya Ce Mamat beserta para pimpinan yang lainnya, seperti Alirakhman, serta Ahmad Bassaif. Atas tertangkapnya Ce Mamat serta pembubaran Dewan rakyat beserta seluruh unsur yang ada, maka segera pemerintahan dikembalikan kepada K.H. Akhmad Khatib. Atas adanya penumpasan terhadap gerakan Dewan Rakyat tersebut, terlihat jika ulama bagi masyarakat Banten lebih mendapatkan tempat dibandingkan dengan jawara.
Penulis: Ilham Aulia Japra