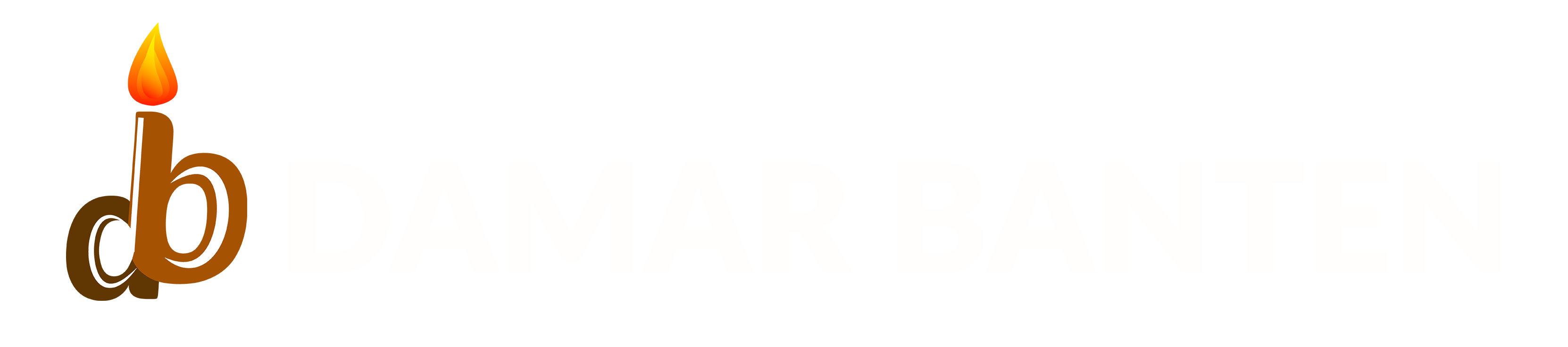Damar Banten – Ketika zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada 1834, saat itu wilayah kesultanan Banten dibentuk menjadi suatu karesidenan yang meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang, serta Lebak. Jabatan tertentu seperti Residen dan seorang Kontrolir, selalu dijabat oleh orang Belanda. Sementara jabatan mulai dari Bupati hingga ke bawah, dijabat oleh orang pribumi.
Sistem pendidikan yang terjadi di masa Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa Barat, baru didirikan pada tahun 1850, yaitu sekolah kelas I. Sekolah tersebut hanya diperuntukan untuk kalangan anak-anak di lingkungan Pangreh Praja saja, serta letaknya berada di ibu kota Karesidenan, seperti Serang, Bogor, Bandung, serta Cirebon. Pada tahun berikutnya, tepatnya di 1951, dibangun sebuah sekolah kelas II yang sifatnya lebih sederhana dan rendah. Kedua kelas tersebut tidak memiliki kaitan dengan sekolah yang lebih tinggi. Barulah di tahun 1875, di Jawa Barat akhirnya dibangun sekolah Hoofdenschool, sehingga lulusan kelas I tersebut bisa diterima menjadi murid yang kemudian dapat menjadi calon Pangreh Praja.
Keputusan pemerintah Belanda di tahun 1852, tentang pendidikan bagi pribumi diterapkan dalam dua prinsip bahasa, yakni bahasa daerah, serta tiga aksara yang harus dipakai di daerah Priyangan semisal, bahasa Melayu dalam aksara Latin, bahasa Arab, serta bahasa Sunda dalam aksara Jawa.
Aktivitas pendidikan di Banten sebelum berdirinya pemerintahan Kolonial, hanya dilakukan di pesantren-pesantren serta langgar-langgar yang berada di wilayah pemukiman masyarakat. Saat itu, mayoritas dari masyarakat Banten hampir semaunya memeluk agama Islam, sehingga pendidikan bagi orang pribumi hanyalah sebatas mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Akhirnya, pada tahun 1899 terbit sebuah artikel yang ditulis oleh Van Deventer, yang berjudul ‘Hutang kehormatan’, pada majalah De Gids. Di dalam artikel tersebut, Van Deventer mengungkapkan keuntungan dari Hindia Belanda yang selama ini seharusnya dibayar ke Negara.
Dari artikel yang ditulis Van Deventer tersebut ternyata cukup berdampak bagi pemerintahan Kolonial. Pada akhirnya, Hindia Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah Politik Etis, atau juga disebut Politik Balas Budi bagi masyarakat pribumi.bKebijakan tersebut adalah suatu pemikiran yang meberikan pernyataan jika Pemerintah Kolonial memegang tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan pribumi. Pemikiran tersebut merupakan kritik terhadap Politik Tanam Paksa yang dilakukan selama ini. Pada tahun 1900, Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief), serta C. Van Deventer (politikus), yang ternyata telah membuka mata atas Pemerintah Kolonial Belanda, agar lebih memperhatikan nasib pribumi yang kehidupannya sangat terbelakang.
Akhirnya, pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta, menegaskan pada pidato pembukaannya di Parlemen Belanda, jika Pemerintah Belanda merasa memiliki panggilan moral, serta hutang budi (een eerschuld) terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tersebut pada sebuah kebijakan yang disebut Politik Etis, yang terangkum di dalam program Trias Politika. Program pertama tersebut di antaranya adalah Irigasi (pengairan), membangun serta memperbaiki pengairan-pengairan, juga bendungan guna keperluan pertanian. Program kedua adalah Emigrasi, yaitu sebuah ajakan untuk penduduk melakukan transmigrasi, guna penduduk tidak saja menggarap lahan untuk kerja hanya berpusat pada satu tempat saja. Program yang ketiga adalah bidang pengajaran serta pendidikan (Edukasi).
Pengaruh politik etis pada bidang pengajaran serta pendidikan sangat berperan besar dalam pengembangan dan perluasan akses pendidikan di wilayah Hindia Belanda. Salah satu dari pihak yang sangat berjasa dari kelompok etis, merupakan Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Berkat peran dari kelompok etis tersebut, akhirnya sejak tahun 1900, berdiri sekolah-sekolah, yang diperuntukkan tidak saja bagi kaum priyayi, akan tetapi juga bagi rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Perkembangan dari dunia pendidikan di Banten pada masa Kolonial, justru berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat Banten.

Sebelum adanya kebijakan tentang politik etis, Pendirian atas sekolah-sekolah di Banten, mulanya hanya ditujukan bagi anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di daerah Karesidenan Banten, baik yang bekerja di pabrik ataupun yang bekerja sebagai Pegawai Pemerintahan di Hindia Belanda. Sekolah bagi golongan pribumi dengan menggunakan bahasa Belada terdapat di Serang, Cilegon, Pandeglang, serta Rangkasbitung.
Anak-anak pribumi dapat mengenyam pendidikan di Bumiputera (Inlandsche School), kelas dua (Tweede Klasse), juga yang dikenal dengan Sekolah Angka Loro, atau di Sekolah Desa, dan Sekolah Rakyat (Volksschool).
Untuk Sekolah Desa, pertama kali didirikan di Hindia Belanda pada tahun 1907. Sekolah semacam itu pada awal abad ke-20 jumlahnya sudah cukup banyak di Karesidenan Banten. Hadirnya sekolah-sekolah Barat di Karesidenan Banten, memiliki perananan yang sangat besar dalam melahirkan elit modern. Mereka merupakan kelompok terpelajar yang ikut berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, dan menjalankan fungsinya, ketika sebagian besar masyarakat pribumi belum dapat mengenyam pendidikan modern. Fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh elit modern di Banten antara lain adalah sebagai dokter, guru, juru rawat, serta lainnya. Bupati-bupati di Karesidenan Banten pada abad ke-20 merupakan elit terpelajar, hasil dari didikan sekolah barat, seperti halnya Bupati Banten Lor, Ahmad Djajadiningrat, sebagai alumni Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yang merupakan sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera di Serang Banten.
Namun, sebelum mengenyam pendidikan di OSVIA, Ahmad Djajadiningrat mendapatkan pendidikan terlebih dahulu di pesantren, serta melakukan kursus privat tentang cara menulis dan membaca huruf Belanda. Setelah bekerja, dirinya juga lantas melanjutkan pendidikan ke Bestuurschool di Jakarta. Sekalipun terlihat cukup baik atas tujuan dibangunnya berbagai macam bentuk-bentuk persekolahan di Hindia Belanda, akan tetapi, dalam prakteknya terdapat kecenderungan yang diskriminatif. Kecenderungan tersebut terlihat pada hal ketika pendaftaran calon peserta didik. Mereka memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, bahkan sering mengutamakan keluarga dari
Kalangan keturunan darah biru, seperti anak Ningrat, keluarga Kraton, serta keluarga priyayi.
Akhirnya, akses pendidikan hanya bisa didapatkan bagi kalangan masyarakat bawah yang mampu dan kaya saja, yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sayangnya, kebaikan dari pemerintah kolonial tidak semata-mata ditujukan untuk pemberdayaan pendidikan kepada masyarakat, akan tetapi untuk menghasilkan tenaga birokrat berdasarkan level pendidikannya, agar dapat direkrut Ke dalam jabatan-jabatan teknis di Pemerintahan Kolonial Belanda.
Sebagai contoh, sejak tahun 1864, Belanda sudah meintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yakni sebuah program ujian pegawai rendah yang perlu ditempuh oleh seseorang agar bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah. Karenanya, terlihat jelas jika program tersebut hanya sebatas untuk menciptakan birokrat rendahan. Ditambah, setelah tahun 1900, diperkenalkan sebuah sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yakni merupakan sebuah sekolah yang dipersiapkan guna menjadikan masyarakat pribumi, sebagai pegawai pemerintah. Dengan begitu nampak jelas kesan jika kegiatan pendidikan bagi pribumi adalah sebatas untuk kepentingan kelancaran ekonomi, serta politik Belanda semata.
Pendidikan para Pangreh Praja Belanda diterapkan pertama kali di Akademi Kerajaan (Koninklijke Akademie), di Delft, pada 17 Juli 1842, berdasarkan Keputusan Raja. Selanjutnya, karena dirasa perkembangan yang cukup pesat di Hindia Belanda, Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan agar melibatkan universitas terkemuka seperti Universitas Leiden, serta Utrecht sebagai tempat mendidik para calon Pangreh Praja. Pada tahun 1879, didirikan sebuah sekolah oleh pemerintah di Bandung, yang diberi nama dengan Opleidings-school Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), di Bandung, yang masa pendidikannya yaitu selama lima tahun. Pada zaman itu, masyarakat pribumi menyebutnya sebagai ‘Sukola Menak’. Peserta didik yang berada di OSVIA merupakan anak para priyayi seperti Bupati, Patih serta Wedana.
Murid OSVIA merupakan lulusan sekolah dasar kelas I. Di Banten, Serang, sendiri, hanya terdapat dua sekolah, sehingga dapat dibentuk OSVIA guna untuk memenuhi kebutuhan atas pegawai Hindia Belanda di Serang, karena pada saat itu, Serang merupakan pusat pemerintahan Kolonial yang ada di Banten. Tujuan dari dibangunnya lembaga pendidikan oleh Belanda, merupakan agar dapat mendidik tenaga kerja yang akan mengerjakan
kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Kepentingan tersebut tidak lain adalah untuk mecari pegawai yang murah, serta bisa dijadikan sebagai pegawai tanpa harus mendatangkan pegawai dari Negeri Belanda.

Oleh sebab itu, Belanda kemudian mendirikan sebuah sekolah Pangreh Praja di Serang, guna memenuhi kebutuhan atas pegawai dengan harga yang murah. Belanda bertujuan untuk memajukan pemerintahannya dengan menggunakan tenaga bumiputera, yang diangkat menjadi kepala pemerintahan berdasarkan keturunan, di Banten banyak keturunan yang berasal dari sebuah kerajaan, oleh karenanya, Belanda kemudian membangun sebuah sekolah untuk anak anak raja yang disebut OSVIA. Sekolah tersebut diperuntukan untuk anak-anak raja, dimana sistem pendidikan di OSVIA menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu, serta Bahasa Belanda. Lulusan dari sekolah tersebutlah yang kemudian akan menjadi pegawai di Hindia Belanda sebagai ‘Regent’ (Bupati).
Jabatan yang diterima sebagai seorang pegawai pemerintah, sangatlah dihargai di masa Kolonial yang birokratis. Pegawai pemerintah adalah pendukung dari otoritas kekuasaan pemerintah Belanda. Jalan keluar agar mendapatkan pekerjaan bagi kaum pribumi di pemerintahan serta perusahaan barat, adalah dengan bersekolah di OSVIA, sehingga sekolah seolah menjadi jenjang karir agar dapat menjadi pegawai di Pemerintahan Hindia Belanda.
Berdirinya sebuah lembaga pendidikan bernama OSVIA, memberiakan banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat Banten. Di maba rakyat Banten dapat merasakan pendidikan yang bergaya Barat, siswa belajar membaca, menulis, berhitung, serta melaksanakan administrasi, ilmu hukum, bahkan dapat menguasai bahasa Belanda atau bahasa asing lainnya. Karenanya masyarakat Banten banyak yang kemudian menyekolahkan anak-anaknyq di sekolah OSVIA, mereka beranggapan jika dengan bersekolah di OSVIA, bisa meningkatkan derajat keluarga, serta kemudian bisa menjadi seorang pegawai yang di hormati oleh rakyat Banten.
Pada 1913, Pemerintah Kolonial Belanda membuat beberapa peraturan mengenai pengangkatan bupati, yang isinya menyatakan, jika keturunan tidak menjadi syarat utama untuk menjadi seorang bupati, yang artinya, tidak saja anak/kerabat dari bupati yang dapat menjadi pejabat tinggi Pangreh Praja. Syarat yang terpenting bagi para calon bupati tersebut, ialah pernah berdinas dengan hasil kerja yang memuaskan selama dua tahun menjadi wedana, dan mahir berbahasa Belanda, dengan pendidikan sekurang-kurangnya setingkat ijazah OSVIA.
Sayangnya, peraturan tersebut tidak begitu mudah, sebab adanya kritikan dari para elite priyayi serta para bangsawan Banten, yang mengajukan keberatan atas peraturan tersebut. Para ellit Priyayi memberikan tanggapan jika peraturan tersebut bertentangan dengan asas pewarisan jabatan.
Ternyata, hanya sebagian elite priyayi berpendidikan yang berani protes secara langsung. Sebagai lainnya melakukan protes dengan cara membuat tulisan dalam bentuk karya sastra. Sebaliknya reformasi pendidikan atas aturan mengenai syarat menjadi bupati, disambut dengan penuh gembira oleh para Ambtenar, yang bukan berasal dari keturunan Ningrat. Koran pribumi kemudian membuat berita mengenai masalah pro-kontra pada peraturan penghapusan asas pewarisan, sehingga Pemerintah Kolonial mengganti peraturan tersebut pada tahun 1921, dengan menetapkan pengangkatan bupati baru berdasarkan asas keturunan, dengan memenuhi persyaratan minimal lulusan OSVIA.
Pemerintah Hindia Belanda menginginkan sebuah birokrasi yang modern, yang kemudian menekankan perekrutan bagi para pejabat berdasarkan asas kualifikasi profesional, promosi atas asas senioritas, keahlian, serta prestasi. Sementara itu di lain pihak, birokrasi pribumi yang patrimonial menekankan jika perekrutan untuk pejabat, harus berdasar hubungan kekerabatan antara para bupati. Akhirnya, dengan terjadinya pergeseran antar elite, kaum Ningrat serta Menak tidak lagi menjadi pemain utama pada panggung politik di Banten. Akan tetapi, justru setelah dibukanya sekolah OSVIA di Banten, Belanda menekankan jika pendidikan akan menjadi suatu prioritas utama dalam pergantian sebuah rezim yang baru.
OSVIA juga telah mengubah paradigma para pelajarnya, jika keluarga pegawai rendah, atau bahkan ayahnya tidak bekerja di Pemerintahan Belanda, dapat menyekolahkan anak di OSVIA tanpa memandang dari status sosial masyarakat. Lulusan dari OSVIA kemudian membentuk sebuah paradigma baru mengenai Pangreh Praja yang dipandang sebagai inti kepegawaian sipil modern di masa selanjutnya. Hal demikian dapat dilihat dari para pejabat yang lebih tua serta kurang tinggi pendidikannya mulai pensiun, maka lulusan dari OSVIA tersebutlah yang akan semakin menjadi ciri korps, serta adanya pergerseran sosial pada kalangan pelajar. OSVIA memberi petunjuk jika para Pangreh Praja di masa mendatang akan semakin berkurang sifat aristokratisnya.
Ketika semakin dalamnya kekuasaan atas Kolonial di Hindia Belanda, maka semakin nampak jelas juga jika kaum Pangreh Praja, yang terdiri dari para bupati serta aparatnya, hanyalah berperan sebagai perantara Pemerintah Kolonial dengan rakyat. Pangreh Praja justru tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan Pemerintah Kolonial, rakyat malahan merasa Pangreh Praja justru tidak berguna sama sekali, karena hak-hak atas Rakyat tidak pernah didengarkan, bahkan Pangreh Praja hanya kepentingan Kolonial semata.
Penulis : Ilham Aulia Japra