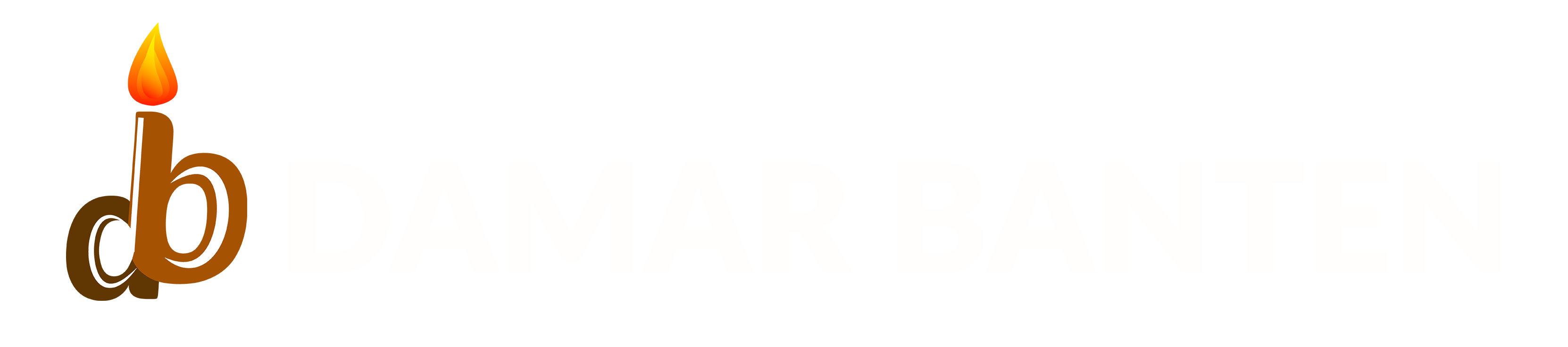Damar Banten – Ketika masa kolonial berkuasa, kebanyakan dari para petani di Tangerang hanya berfungsi sebagai penggarap sawah serta ladang, yang dimiliki oleh para tuan tanah. Hal demikian bisa terjadi akibat wilayah Tangerang yang menjadi wilayah partikelir, yang kala itu dimiliki oleh sebagian orang-orang kaya yang berprofesi sebagai pengusaha terpandang. Kondisi pertanahan semacam itu justru tidak membuat nasib para petani menjadi lebih baik, akan tetapi malah semakin membuat beban hidup mereka semakin berat, akibat di tanah partikelir penguasanya merupakan para tuan-tuan tanah yang memiliki hak absolut atas lahannya.
Para tuan-tuan tanah tersebut juga bisa dengan bebas melakukan apapun, ditambah para petani penggarap juga harus dibebani oleh kewajiban-kewajiban lain yang sangat memberatkan, semisal membayar cuke, yang kala itu besarannya merupakan seperlima atas hasil panen yang didapatkan, pembayaran sewa tanah pada lahan yang digarapnya, kebutuhan akan pemukiman, pekarangan, tegalan, bahkan kerja wajib bagi pemeliharaan fasilitas umum, yang semua hal tersebut tidak dapat ditolak. Dalam Kerja wajib, hal tersebut tidak bisa dihindari begitu saja karena hukuman untuk orang yang menghindarinya sangat memberatkan, yakni harus membayar denda uang dengan jumlah yang telah ditentukan, serta jika kewajiban denda tersebut tidak dibayarkan dan mangkir dari pekerjaan wajib itu, maka pelanggar tersebut akan dituntut ke pengadilan serta bisa dikenakan sanksi pidana. Jika kelompok petani berasal dari masyarakat pribumi, hal demikian berbeda pada kalangan tuan tanah yang umumnya berasal dari etnis Tionghoa. Sekalipun ada beberapa yang berasal dari etnis Arab, akan tetapi jumlah pemilik tanah partikelir yang berasal dari bangsa Timur Asing jauh lebih banyak.
Pada pemilik tanah yang beretnis Tionghoa, secara umum biasa disebut dengan istilah teko, serta karena hal demikian juga selanjutnya lahan yang dimiliki oleh seorang tuan tanah dari Tionghoa, dikenal dengan sebutan istilah “tanah teko”. Lahan yang dimiliki oleh para tuan-tuan kaya tersebut dikelola oleh sumber daya dari kaum pribumi, yang memang dengan sengaja dipekerjakan guna mengurusinya. Istilah “bujang-bujang sawah” merupakan penyebutan yang ditujukan terhadap orang-orang yang tenaganya dipakai oleh pemilik lahan, guna sebagai kepentingan pertanian serta perkebunan yang terjadi pada masa itu.
Akibat dari tanah partikelir serta kekayaan yang dimiliki oleh tuan tanah tersebut dapat diwariskan, pada akhirnya tidak heran jika keturunan dari seorang juragan tanah akan tetap kaya selama beberapa generasi kedepan. Karena kekayaannya yang dimilikinya sangat melimpah, biasanya tuan-tuan tersebut akan menjadi seseorang yang terpandang di wilayahnya. Pada lima masa perekonomian di era kolonial Belanda, hampir semuanya itu dapat dipastikan tidak ada kebijakan yang benar-benar berpihak terhadap masyarakat pribumi, yang kala itu sebagian besarnya merupakan kaum petani. Kelompok petani tersebut, pada akhirnya banyak yang dikapitalisasi secara penuh oleh kaum kapital, entah dari unsur pemerintah kolonial hingga kroni-kroninya, yang pada dasarnya hanya berorientasi terhadap keuntungan semata.
Pada konteks tersebut, petani yang mayoritas merupakan penduduk asli bumiputera, memang benar-benar dibuat tidak berdaya di tanah sendiri. Sekalipun telah ada rintisan peraturan tentang perlindungan hak serta kepentingan bagi petani dari gerak-gerik para kaum pemilik modal, serta tuan tanah pada masa Daendels dan Raffles, akan tetapi Hal demikian tidak mudah untuk diberlakukan. Terlebih, pada kondisi keuangan negara yang sedang mengalami banyak pengeluaran, sehingga membuat kebijakan idealis tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perilaku atas tuan tanah, tidak jarang menjadi resiko konflik yang serius di antara para petani dengan tuan tanah. Perilaku dari para tuan tanah yang semena-mena terhadap para petani, sering kali menyebabkan keresahan di antara mereka, yang akhirnya rasa tersebut semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga terakumulasikan pada bentuk amarah yang tidak lagi dapat ditahan. Rasa tersebut pada akhirnya mengarahkan para petani agar melakukan gerakan protes, bahkan perlawanan yang serius terhadap para tuan tanah. Para petani sudah muak terhadap nasib serta kehidupan mereka yang tetap diinjak-injak oleh kesewenang-wenangan para tuan tanah. Protes yang dilakukan oleh para petani dapat diluapkan ke dalam berbagai macam bentuk ekspresi. Dua di antaranya merupakan dalam bentuk tindak kejahatan serta pemberontakan massal.
Tindakan pertama atas respon dari kesewenang-wenangan kemudian diluapkan dalam cara yang negatif seperti membunuh, atau merampok para tuan-tuan tanah. Di samping itu, respon kedua merupakan pemberontakan yang biasanya dirintis oleh seorang tokoh kharismatik, guna mengubah nasib buruk para petani. Salah satu wilayah yang tanahnya kala itu banyak dimiliki oleh tuan tanah, ialah Tangerang. Tangerang memang sengaja dijadikan Kawasan Tanah Partikelir oleh kolonial. Tangerang pada saat itu dipandang sebagai wilayah yang sangat strategis di barat Karesidenan Batavia, karena posisinya yang secara geografis dapat menjadi daerah untuk penghubung antara Batavia dengan wilayah kesultanan Banten.
Sebelum menjadi bagian dari VOC, Tangerang adalah wilayah di ujung timur Kesultanan Banten. Sayangnya, ketika kesultanan Banten berhasil diobok-obok oleh Daendels, Tangerang akhirnya menjadi pusat ekonomi serta politik karena posisinya yang diapit oleh sungai Cisadane, Tangerang akhirnya dijadikan sebagai salah satu bagian terpenting dari Batavia. Asal usul kata Tangerang diyakini berasal dari bahasa Sunda yakni “Tengger” dan “Perang”. Tengger bermakna Tugu atau tempat peringatan sesuatu yang umumnya dibuat dari bambu, batu, atau bisa juga berbentuk benteng. Hal demikian mendasari kenapa dulu Tangerang dikenal juga dengan nama Benteng, yang juga merujuk pada bangunan benteng di sepanjang sungai Cisadane. Sementara untuk kata Perang, yaitu berarti sebuah kejadian besar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih kelompok yang saling bertikai, serta tengah melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan saling berhadapan, pertempuran atau pun perang. Kendati demikian, terdapat pendapat lain yang menguraikan mengenai asal muasal kata Tangerang yang berasal dari penelitian M. Dien Madjid beserta timnya terhadap manuskrip-manuskrip kuno. Menurut uraiannya tersebut, dapat diketahui Jika kata Tangerang berasal dari sebuah kata berbahasa Sunda, yaitu “tangeran” yang artinya adalah “tanda.” Yang dimaksud dengan tanda itu, dapat dimaknai sebagai sebuah tugu karena pada masa Kesultanan Banten, wilayah Tangerang pernah “ditandai” atau dijadikan “tugu” perbatasan antara wilayah mereka dengan VOC. Kemudian kata “Tangeran” yang berasal dari Bahasa Sunda tadi yang pelafalannya menjadi “Tangerang”, karena mendapat pengaruh dari bahasa Makassar, yang tidak mengenal huruf mati pada akhir kata. Status tanah di Tangerang ketika masa Kesultanan Banten, adalah Tanah Negara yang merupakan tanah milik Sultan. Tanah tersebut digarap oleh para petani dengan kewajiban membayar pajak serta tenaga kerja. Sementara itu, ada beberapa jenis lain tanah pada masa tersebut yang memiliki status berbeda satu sama lain. Bagi tanah yang diberikan Sultan terhadap keluarga raja serta para birokrat kesultanan, disebut dengan tanah ganjaran, pusaka laden, atau pecaton. Sedangkan tanah yang memang secara khusus dianugerahkan kepada keluarga raja dikenal dengan nama kewargaan atau kanayakan, serta untuk tanah bagi jajaran birokrat yang bekerja kepada kesultanan dari tingkat terendah hingga pada tingkat tertentu disebut dengan tanah pangawulaan. Pemberian tanah semacam itu merupakan hak serta kewenangan yang mutlak bagi seorang sultan pada masa itu, serta biasanya hanya diberikan terhadap orang-orang tertentu saja yang dirasa memiliki jasa terhadap Sultan.
Tanah-tanah yang digarap oleh para petani tidak saja berasal dari kebijakan kesultanan, akan tetapi juga berasal dari tanah yang dimiliki oleh para pembesar dari kalangan bangsawan serta para birokrat tersebut. Tanah milik mereka itu diberikan guna dikelola oleh para petani serta mereka nantinya akan mendapat bagian dari panen yang dihasilkan. Ada juga tanah kosong milik kesultanan yang kemudian dimanfaatkan guna pembukaan sawah, tanah itu disebut dengan istilah Tanah Yasa. Semua tanah-tanah tersebut tidak saja menjadi sumber penghasil bagi para pemiliknya, namun juga termasuk sebagai sumber penghasilan pajak negara, sehingga semakin luas lahan yang dikembangkan, maka semakin banyak juga pendapatan kenegaraan yang didapatkan oleh kesultanan.
Ketika berubahnya konstelasi politik serta kekuasaan di wilayah Banten, mengakibatkan perubahan atas status tanah yang ada. Pada saat VOC mulai memegang kendali di Banten, maka banyak dari tanah yang kemudian diberikan atau dijual kepada orang-orang asing (terutama orang Tionghoa). Status kepemilikan tanah dengan pola semacam itu terus berjalan hingga pada masa-masa akhir Hindia Belanda. Sialnya, status pertanahan dengan keadaan semacam itu, justru tidak memiliki imbas yang signifikan bagi kalangan masyarakat rendahan seperti petani penggarap. Di tanah-tanah tersebut, mereka justru hanya dijadikan sebatas objek eksploitasi para pemilik tanah. Istilah Tanah Partikelir (particuliere landerijen) yang ada di wilayah Tangerang, sudah ada sejak zaman VOC. Pada masa tersebut, terdapat kebijakan guna memperjualbelikan tanah terhadap pihak swasta untuk keuntungan perusahaan atau kompeni.Selain orang-orang Eropa, pihak swasta yang juga memiliki banyak tanah partikelir berasal dari kalangan orang Tionghoa. Sekalipun terdapat beberapa perubahan tertentu, ternyata status atas tanah partikelir yang ada tetap tidak berubah hingga mendekati akhir masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Status tanah partikelir tersebut bersifat mutlak, karena penjualnya dari pihak kompeni atau pemerintah kolonial, memberi keleluasaan bagi mereka guna mengolah tanahnya secara total termasuk orang-orang didalamnya. Dalam artian, pihak yang membeli tanah partikelir tersebut tidak saja
mendapatkan sebidang tanah, akan tetapi juga mendapatkan hak-hak guna membentuk satuan pengamanan daerah di tanahnya, bahkan juga berhak dalam menarik pajak atas
petani yang berada di dalamnya.Intinya, para tuan tanah (landheer) memiliki Hak Keistimewaan (Hak Pertuanan) pada tanah yang dimilikinya. Dengan begitu, penduduk yang tinggal atau menjadi penggarap di tanah mereka, diharuskan untuk tunduk kepada penguasa tanah partikelir. Nomenklatur tanah di wilayah Tangerang kala itu, terbagi menjadi dua macam, pertama, tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha yang disebut dengan erfacht, kedua, tanah yang dikenal dengan istilah landsdomein atau tanah negara. Peraturan soal tanah tersebut dibentuk guna mengatur kepemilikan atas tanah perseorangan. Sementara untuk tanah usaha (erfacht) di daerah Tangerang, berada di Distrik Tangerang serta Distrik Mauk Selain itu, ada juga pembagian tanah dengan istilah persil (bidang atau bagian tanah). Sebetulnya, tanah partikelir di Tangerang antara tahun 1900-1901 terdiri atas 18 persil dengan kepemilikan yang bervariasi. Tanah-tanah tersebut, selain juga dimiliki oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, juga dimiliki oleh perusahaan dan pribadi. Guna kepemilikan yang bersifat privat atau individual, di samping para tuan tanahnya berasal dari etnis Tionghoa, terdapat juga etnis lain yang di antaranya adalah bangsa Arab.Penulis : Ilham Aulia Japra