Damar Banten – Tidak pernah disangkakan bahwa peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Kolonial Belanda, ke Pemerintahan Pendudukan Jepang dianggap memberikan harapan bagi bangsa Indonesia yang sedang mati-matian meraih kemerdekaan. Keberhasilan dari pasukan Kamikaze atas penaklukan pasukan militer Belanda di tahun 1942, menjadi penyulut semangat bagi pejuang kemerdekaan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda.
Di awal kehadiran Jepang ke Nusantara dapat dikatakan sangat diterima dengan tangan terbuka, bahkan dielu-elukan oleh masyarakat Nusantara sebab, dianggap sebagai saudara tua yang telah membantu bangsa Indonesia, keluar dari cengkeraman penjajahan Belanda. Bahkan Simbol-simbol bangsa Indonesia saat itu diperbolehkan untuk dipasang berbarengan dengan simbol-simbol negara Jepang. Bendera merah putih berkibar bersebelahan dengan bendera matahari terbit, sementara itu juga, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang. Selanjutnya, Jepang juga membantu membebaskan tokoh-tokoh nasional yang kala itu ditahan oleh Belanda.
Hal tersebut dilakukan Karena prinsip utama yang dipegang oleh Jepang, ketika menguasi
Nusantara, terlebih Jawa, yakni strategi untuk menarik hati rakyat (minshin ha’aku), serta untuk mengindoktrinasi; menjinakkan mereka (senbu kosaku), sampai mengusahakan agar daerah yang diduduki dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Hal tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.
Ketika semakin melebarnya serangan Sekutu atas wilayah-wilayah yang sedang diduduki oleh Jepang, hal tersebut kemudian membuat Pimpinan Tentara Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Harada, untuk mengambil keputusan agar melakukan perlawanan dalam bentuk aksi-aksi lokal, jika suatu saat Pasukan Sekutu mendarat di Jawa. Jenderal Harada paham betul, jika Tokyo tidak akan mengirimkan divisi-divisi baru untuk membantu pertahanan di Jawa.
Kendati demikian, diambilah sebuah keputusan bahwa setiap Karesidenan yang berbeda di Jawa, diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing serta menyimpan perbekalan, bahkan perlengkapan perang. Pada saat masa pendudukan Jepang di Jawa, Petinggi Militer diharuskan untuk memiliki kemandirian, terutama kemandirian pada bidang energi. Hal tersebut diakibatkan atas kebutuhan yang tinggi terhadap sumber energi Industri, berupa batu bara yang selama ini didatangkan dari Sumatera dan Kalimantan. Dalam kondisi tersebut, sangat tidak memungkin untuk dilakukan pada masa perang, sebab kapal tongkang yang membawa batu bara pasti akan menjadi sasaran empuk bagi torpedo-torpedo Angkatan Laut Sekutu.
Dalam situasi tersebutlah, yang akhirnya mendorong untuk melakukan eksploitasi potensi atas batu bara di Bayah, yang bertujuan supaya Jawa bisa mandiri secara energi. Pada akhirnya kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan di Bayah, dilaksanakan dengan tiga tahapan, yakni tahap perencanaan serta pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 1942 hingga 1943, dan tahap produksi atau penambangan yang dilakukan sejak tahun 1943 hingga Jepang kalah di bulan
Agustus, 1945.
Di masa tahap awal perencanaan pertambangan batu bara di Bayah, dilakukan sebuah survei serta pemetaan guna menemukan serta menandai tempat-tempat yang potensial mengandung batu bara dengan kualitas yang tinggi dan memungkinkan dapat eksploitasi secara penuh. Sedangkan pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap pembangunan, aktivitas yang dilakukan merupakan kegiatan untuk pembukaan hutan agar dapat dijadikan sebagai areal tambang dan permukiman pekerja—penggalian terowongan utama pada blok Madur, Blok Cihara, serta Blok Cimang—Pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api Saketi—Bayah (RG 1067), jalur kereta tambang atau Stingkul (RG 700)—serta pembangunan infrastruktur pendukung perusahaan tambang lainnya, semisal perkantoran, perumahan pegawai, gardu induk listrik, sarana air bersih, hingga rumah sakit.
Pada saat pembuatan atas jalur kereta api lintas Saketi-Bayah, akhirnya dibangun dengan rangka-rangka rel hasil dari bongkaran jalur lama yang tidak aktif serta tidak efisien. Ketika pada tahap produksi penambangan, sebelumnya telah ditetapkan lokasi-lokasi untuk para penambang, seperti di Blok Madur, Cihara, serta Cimang. Batu bara yang kemudian dihasilkan, langsung diangkut ke pusat-pusat penampungan menggunakan kereta api RG (Rail Gauge) 700 atau Stingkul (kereta tambang).
Kemudian di tempat pusat-pusat penampungan, batu bara langsung diangkut menuju luar Bayah dengan menggunakan kereta api RG 1067. Saat itu, jalur kereta api dibangun dari stasiun saketi pada jalur Rangkasbitung—Labuan hingga ke pusat pertambangan batu bara yang berada di Bayah. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan dari batu bara yang berada di Bayah, salah satunya merupakan Blok Madur atau Gunungmadur.
Pada Blok Madur, menjadi blok penambangan terbesar pada kawasan pertambangan Bayah Kozan. Di kawasan tersebut banyak sekali ditemukan lubang bekas tambang batu bara dengan berbagai macam ukuran. Bahkan, di lokasi penambangan yang besar tersebut , lubang juga terowongan utama memiliki kedalaman hingga 100 sampai 750 m, dengan tipe lubang Horizontal. Mulut lubang berukuran 2,5 hingga 3,0 m, serta di dalamnya terdapat kamar-kamar serta lorong-lorong cabang.
Untuk penyangga dinding atau atap terowongan, digunakan kayu sebagai penyangganya. Di bagian bawahnya terdapat rel lori sebagai pengangkut batu bara. Dapat dikatakan, lubang dan terowongan pada tambang batu bara di Bayah, terbagi menjadi dua bagian, pertama lubang totoire serta yang kedua adalah lubang jibangso. Pada Lubang totoire
Tersebut, merupakan terowongan utama yang menjadi tempat beraktivitas keluar masuknya romusha serta lori pengangkut batu bara. Sedangkan pada Lubang jibangso, adalah jalur-jalur sempit pada totoire guna menambang batu bara.
Untuk romusha yang bekerja di penambangan, kemudian diklasifikasikan pada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 10 sampai 12 orang pada setiap kelompoknya. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang kepala regu yang beranggotakan dari 2 orang pemegang bor, 2 orang ahli dinamit, serta sisanya merupakan pemecah batu atau tukang angkut. Aktivitas penambangan dilakukan dengan meledakkan ader menggunakan dinamit. Pecahan disertai reruntuhan batu bara yang berupa bongkahan, kemudian dikumpulkan dan dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil, yang selanjutnya akan ditampung pada lori yang akan mengangkutnya ke luar lubang. Di banyak titik ader, terutama yang ukurannya kecil, penambangan dilakukan secara manual dengan cara menghancurkannya menggunakan belincong.
Ketika sudah banyak terkumpul, kemudian batu bara diangkut menuju pusat penimbunan yang berada di stasiun Bayah, dengan menggunakan stingkul. Hingga saat ini, di antara lubang-lubang pada tambang masih dapat ditemukan di Gunung Madur, hingga masyarakat sekitar menyebutnya sebagai lubang Jepang. Di antara lubang-lubang tambang tersebut adalah: Lubang Cipicung, Lubang Cigalugur, Lubang Sangko, serta Gua Jepang di tepi pantai Gua Langgir.
Pada lubang Cipicung, merupakan salah satu lubang tambang yang berada di kawasan Gunungmadur, yang hingga kini dapat dilihat. Lokasi lubang tambang tersebut berada di Kampung Sawah Desa Darmasari, tepatnya di hulu aliran Ci Picung, tidak jauh dari jalan lama penghubung Bayah—Cisolok. Pada kondisi mulut lubang tambang sudah longsor serta pada bagian atasnya terdapat pohon beringin.
Pada bagian pintu masuk lubang, saat ini sudah tertutup longsoran pada bagian tengahnya, yang akhirnya membentuk dua celah yang masih terbuka dengan ukuran masing-masing lebar 1,25 m dan tinggi 1,50 m. Pada bagian bawah lubang tambang sudah dipenuhi lumpur serta longsoran. Sedangkan pada bagian puncak bukit yang berada di atas lubang Cipicung, ada sebuah lubang vertikal yang menyerupai sumur persegi dengan ukuran 1 x 1 m. Sumur itu adalah lubang tambang yang dibuat oleh masyarakat yang akhirnya tidak dilanjutkan untuk ditambang.
Menurut masyarakat sekitar, sumur itu memiliki kedalaman hingga 6 m disertai lubang mendatar dengan panjang sekitar 6 m mengikuti ader. Ujung lubang yang mendatar tersebut bermuara di lubang Jepang, yakni lubang Cipicung. Pada ruangan yang berada di dalam lubang Jepang tersebut relatif luas, saat ini, penyangga balok-balok kayu sudah rapuh. Padahal untuk batu bara yang tersedia di dalam sangatlah banyak ditemukan, namun, penggalian tidak dapat dilanjutkan akibat tercium bau gas yang sangat menyengat.
Sedangkan untuk Lubang tambang Madur/Cigalugur, letaknya ada di hulu Ci Galugur, yang berada di kawasan perkebunan karet Gunungmadur yang dikelola oleh PT. Perkebunan Kroewoek atau PT. JA Wattie. Lokasi lubang tambang tersebut letaknya tidak jauh dari kompleks perumahan atau kantor Perkebunan, yang tepatnya berada pada dasar lembah Cigalugur. Di masa Pendudukan Jepang, kawasan tersebut adalah pusat administrasi Bayah Kozan cabang Blok Madur. Hingga kini, lubang tambang sudah tidak lagi dapat dikenali, akibat pintu lubang sudah tertutup longsoran material disertai tersebut oleh ilalang dan tumbuhan perdu.
Untuk Lubang Sangko, letaknya berada pada kaki tebing curam di tepi sungai kecil, tepatnya berada di Kampung Sangko Desa Sawarna, Kecamatan Bayah. Lubang Sangko adalah lubang tambang Horizontal dengan mulut lubang berukuran besar. Kini, kondisi mulut lubang Sangko sebagian besar tertutup oleh longsoran dinding gua dengan bagian yang terbuka berukuran tinggi 1,30 m dan lebar 4 m. Pada bagian dalam lubang dipenuhi dengan lumpur hingga menjadi aliran air akibat keberadaan dari mata air di dalam gua.
Yang menarik, ada sebuah gua bernama Gua Hartakarun atau Lubang Jepang , yang merupakan gua buatan yang digali di bagian tebing karst pantai Gua Langir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah. Keberadaan gua Jepang Tersebut tidak jauh dari lubang Sanko, lubang Niko, serta pusat pengumpulan batu bara di Pulomanuk. Gua tersebut adalah gua yang di buat untuk kepentingan pertahanan.
Para penduduk Desa Sawarna menjelaskan bahwa berdasarkan cerita orang
tuanya, gua Jepang dibangun guna dijadikan markas tentara yang bertugas mengintai lautan. Serta, gua tersebut juga dijadikan gudang untuk menyimpan barang-barang yang dikirim melalui laut. Sayang, ketika Jepang akan kalah serta meninggalkan Bayah, gua tersebut akhirnya dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan dinamit, serta para romusha yang bekerja di gua tersebut ikut dikubur, tidak ada seorang pun yang lolos.
Seluruh lubang tambang di kawasan Gunungmadur digali serta ditambang oleh para romusha. Kendati demikian, semua aktivitas pertambangan sejak masa persiapan hingga ke tahap operasional, dilaksanakan menggunakan tenaga dari romusha yang didatangkan
dari berbagai daerah di luar Banten, terutama dari Jawa Tengah bahkan Jawa Timur. Catatan dari Tan Malaka menunjukkan jika jumlah romusha yang berada di Bayah pada tahun-tahun awal, bahkan mencapai 20.000 orang, serta pada menjelang menyerahnya Jepang, jumlahnya berada di sekitaran 10.000 orang.
Dari keahlian yang dimiliki oleh para romusha yang berada di Bayah, kemudian para romusha diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni romusha yang memiliki keahlian serta romusha yang tidak memiliki keahlian. Romusha yang kemudian memiliki keahlian merupakan mereka yang sebelum dikirim ke Bayah, sudah memiliki keahlian seperti masinis, pegawai stasiun, ahli di bidang mesin, survei lahan, ahli konstruksi jalan atau jembatan, hingga ahli dalam penambangan.
Romusha yang tidak memiliki keahlian merupakan mereka yang tidak memiliki kemampuan pada bidang apapun termasuk pertambangan, yang saat itu diperlukan di pertambangan Bayah. Akan tetapi berdasarkan kondisi fisik, romusha dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni kelompok romusha yang kondisi fisiknya lemah, kelompok romusha yang kondisi fisik sedang, serta kelompok romusha yang kondisi fisik yang kuat. Pembagian kelompok
tersebut yang didasarkan terhadap kondisi fisik, ditujukan guna mempermudah pada saat penempatan di pertambangan Bayah.
Sedangkan untuk jenis pekerjaan di Pertambangan Bayah di antaranya ada bagian tambang, bagian transportasi, bagian bangunan, bagian kereta api, bagian bengkel mobil atau kereta api, bagian gudang, hingga pesuruh di kantor atau rumah
orang Jepang. Pengumpulan para romusha awalnya dilakukan secara sukarela serta terdiri dari para pengangguran yang mencari kerja, atau dipekerjakan sebagai tenaga produktif dan buruh, pada saat permintaan akan tenaga kerja terus meningkat, akhirnya, sejak akhir tahun 1943, Pemerintahan Jepang di Indonesia mengorganisir atas tenaga kerja secara sistematik serta intensif lewat slogan “Peningkatan Produksi” dan “Mobilisasi total”.
Perekrutan tidak lagi dilakukan dengan cara mengandalkan perekrutan secara sukarelawan. Akan tetapi pemerintah Jepang memerintahkan kepada kepala desa, agar menyediakan warganya untuk menjadi romusha. Perekrutan atas tenaga kerja juga dilakukan Pasukan Jepang dengan cara menjalankan razia, bahkan mengambil siapapun yang tertangkap di jalan untuk memperkuat barisan romusha, agar mencukupi atas kebutuhan tenaga kerja. Laki-laki atau perempuan yang sudah masuk usia produktif pada setiap desa dipaksa oleh setiap kepala desa, untuk kemudian mereka dikenai wajiban kerja tanpa terkecuali.
Sering sekali sebuah lembaga yang berhubungan langsung dengan romusha, mengkondisikan penempatan romusha sesuai dengan kebutuhan akan angkatan perang. Kebijakan mobilisasi tersebut dimaksudkan guna menciptakan produktivitas akibat pengurangan produktivitas atas pertanian serta perkebunan di Jawa. Bahkan, romusha dikategorikan sebagai komoditi yang diperlukan untuk dipertukarkan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perang. Hal tersebut menunjukkan jika perekrutan atas romusha yang dilakukan secara lebih serius, dengan alasan bahwa kondisi perang yang semakin memburuk untuk Jepan, tuntutan yang terus ada agar dapat mencukupi kebutuhan sendiri (swasembada) untuk setiap Angkatan Perang yang berada di daerah pendudukan, serta adanya motif ekonomi atas setiap pengerahan tenaga romusha.
Awalnya para romusha datang ke Bayah bertujuan agar dapat memperbaiki kehidupan guna menjadi lebih baik, akan tetapi kenyataannya jauh dari ekspektasi mereka. Ketika para romusha menjalani tugas mereka, para romusha dituntut agar bekerja dengan berat disertai peralatan seadanya. Bahwa para romusha juga mengalami banyak siksaan
fisik maupun mental, disertai kurangnya asupan gizi, bahkan kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Banyak sekali kecelakaan kerja yang terjadi di dalam lubang tambang. Para pekerja romusha banyak sekali yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Para romusha harus kehilangan nyawa mereka akibat keracunan gas, tertimpa longsoran, serta bencana lainnya yang terjadi di lubang tambang.
Memang tidak ada catatan pasti mengenai jumlah romusha yang tewas di Bayah, selama
aktivitas pembangunan atau penambangan batu bara, juga pembangunan jalur kereta api
Saketi—Bayah. Di proyek pembangunan jalur kereta api Saketi—Bayah saja, banyaknya romusha yang tewas saja mencapai angka 90.000 jiwa. Mayat-mayat para romusha yang mati acap kali dikuburkan tanpa melalui proses ritual keagamaan. Mayat-mayat romusha hanya dibungkus dengan tikar serta dibalut dengan pakaian yang menempel pada tubuhnya. Bahkan pemakamannya pun dilakukan di lokasi mayat tersebut ditemukan, akibat dari banyaknya mayat romusha yang tewas, sering sekali satu lubang kuburan diisi oleh 5 hingga 10 mayat.
Ada beberapa pemakaman massal romusha berada di Bayah, salah satunya berada di kawasan Deker, Pulomanuk, yang memiliki luas hingga mencapai 38 Ha. Sekarang, wilayah kuburan massal dari para romusha tersebut, menjadi bagian dari kawasan Perkebunan Karet. Para romusha yang tewas di tempat lain, tentu akan dimakamkan di tempat di mana dia tewas. Akibatnya, pada sekitaram lubang Sangko, kampung Sawah, Cimanuk—Cibobos, serta Cimang, juga ada kuburan massal dari para romusha. Ada seorang yang paling sering menguburkan para mayat romusha, terutama pada sekitaran Blok Madur, termasuk juga Pulomanuk, serta Sawarna, ia adalah romusha bernama Amat Parino, seorang romusha asal Purworejo yang bertugas di bagian lubang.
Romusha di Bayah tentu saja menyusun luka menganga terhadap korban serta keluarganya. Hal tersebut yang menjadikan ingatan bersama masyarakat atas tragedi demi tragedi romusha perlahan-lahan dilupakan. Para mantan romusha enggan untuk menceritakan pengalaman mereka selama bekerja atau hidup di Bayah, bahkan terpisah jauh dari keluarga besar. Ketidak inginan mereka dalam bercerita tentang pengalamannya semasa menjadi romusha, diakibatkan mereka ingin melupakan tentang apa saja yang sudah pernah dialami, serta berharap anak cucunya kelak tidak merasakan kejam-kejinya menjadi seorang romusha.
Penulis : Ilham Aulia Japra S.Sos

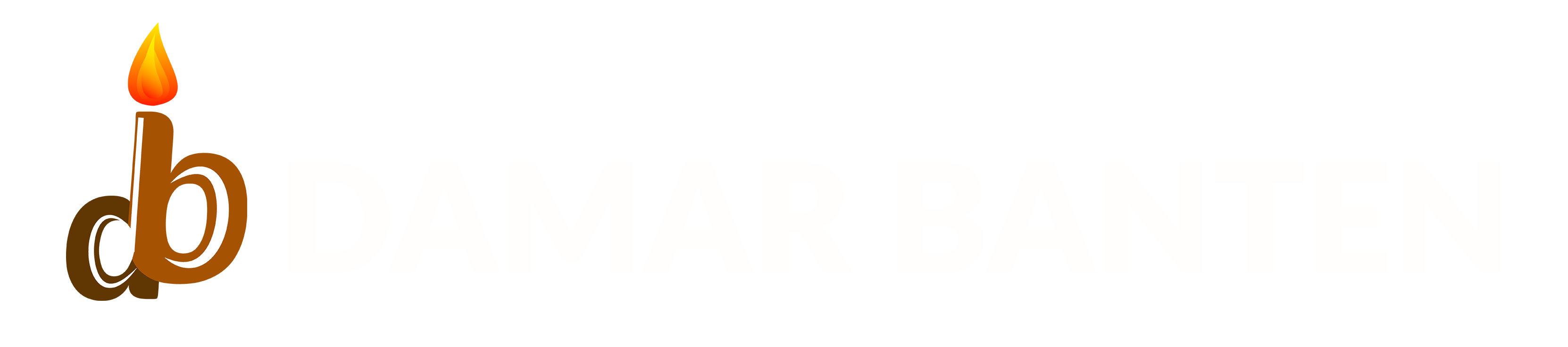






Ini tulisan 99,9% copas