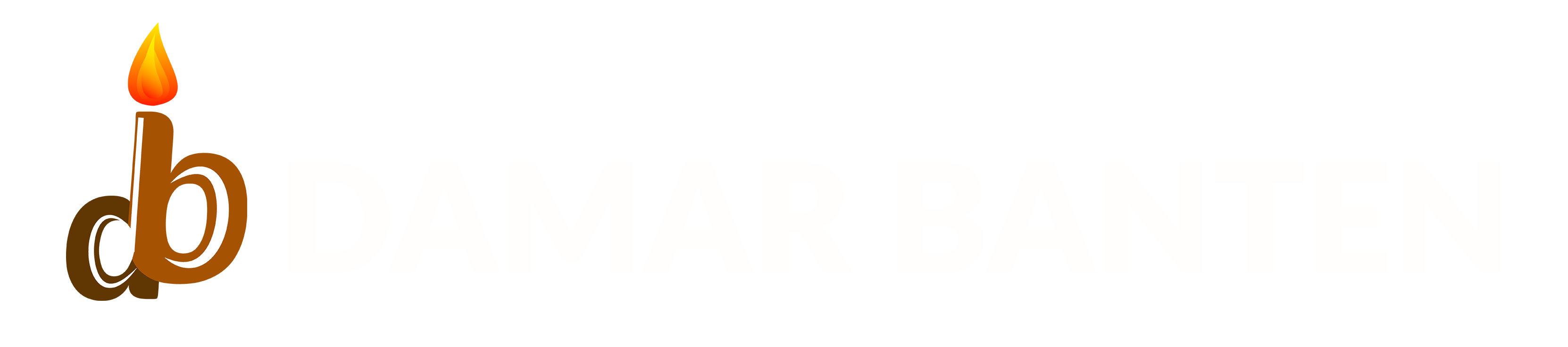Damar Banten – Catatan paling awal yang merekam tentang Prabu Siliwangi secara samar-samar tersirat dalam cerita pantun Langga Larang, Babakcatra, Siliwangi, dan Haturwangi. Keempat cerita pantun tersebut disebutkan di dalam teks Siksa Kandang Karesian yang berbahasa serta beraksara Sunda Kuna, bertarikh 1518 M.
Akan tetapi para peneliti kajian Sunda kehilangan narasi awal tersebut. Pasalnya, keempat cerita pantun itu lenyap tak berjejak. Namun kendati demikian, dengan bukti semacam itu sudah memperjelas jelas, bahwa pada tahun 1518 M Prabu Siliwangi sudah menjadi tokoh cerita pantun.
Yang menjadi menarik, sosok Prabu Siliwangi masih muncul di banyak karya sastra, terutama cerita pantun Sunda di akhir abad ke-16. Seorang linguis asal Belanda, Fokko Siebold Eringa, yang objek disertasinya menggarap cerita pantun Loetoeng Kasaroeng, berhasil menghimpun tiga puluh tujuh judul cerita pantun yang dikenal luas masyarakat Sunda. Akan tetapi dalam banyak cerita pantun tersebut, Prabu Siliwangi justru tidak ditempatkan sebagai tokoh utama yang memiliki peran besar dalam cerita. Sebaliknya, tulis Eringa dalam Loetoeng Kasaroeng: Een Mythologisch Verhaal uit West Java (1949), diterbitkan sebagai seri Verhandelingen van het Koniklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkekunde, (VKI), deel 8. 1949, tokoh utama yang tampil dalam cerita ialah para putranya: Jaka Susuruh, Guru Gantangan, dan Munding Laya Dikusuma.
Hubungan rekam jejak Sang Prabu dalam karya sastra abad ke-16 dengan kenyataan zaman pernah diungkap Jacobus Noorduyn, filolog asal Belanda yang menggeluti beragam naskah Sunda. Jacobus berpijakan pada teks Bujangga Manik yang memuat kekayaan detail topografi wilayah Jawa, Bali, dan berbagai lokasi di tanah Sunda yang dilalui Bujangga Manik, pujangga kelana asal Pakuan.Di saat akan menyeberangi perbatasan Sungai CiPamali (sungai di Brebes), sebagai batas wilayah Sunda dan jawa, Bujangga Manik terlebih dahulu singgah di wilayah Arega Jati dan Jalatunda — keduanya tak dikenali. Teks tersebut menghubungkan Jalatunda, yang biasanya mengacu kepada tempat pemandian (patirthan), sebagai tempat melestarikan kenangan (sakakala) terhadap Siliwangi. Potongan kecil informasi pada teks Bujangga Manik menunjukkan bahwa Siliwangi telah menjadi tokoh historis saat teks tersebut dituliskan.
Narasi yang lebih lengkap mengenai laku hidup Prabu Siliwangi terekam di dalam beberapa manuskrip yang digubah pada abad ke-19: Tjerita Prabu Anggalarang, Babad Pajajaran, Babad Siliwangi, dan Wawatjan Tjarios Prabu Siliwangi. Hanya saja muatan teks pada manuskrip-manuskrip tersebut dirasa kurang dalam artian sebagai sumber sejarah, akan tetapi lebih banyak sebagai karya sastra yang ditulis ke dalam bentuk sebuah tembang.
Prabu Siliwangi tidak saja hanya hidup pada sebuah teks dan rangkaian cerita bela. Namanya pun acap kali digunakan sebagai legitimasi politik para bupati dan bangsawan Sunda. Di dalam berbagai naskah yang kebanyakan ditulis abad ke-19, nama Prabu Siliwangi banyak dimuat sebagai kebutuhan para bupati yang berkuasa di berbagai kabupaten di Jawa Barat, khususnya Priangan, Mereka sangat ingin mengaitkan hubungan trahnya dengan Prabu Siliwangi lewat babad- babad keluarga yang memuat pohon kekerabatan.
Pada sebuah Carita Purwaka Caruban Nagari, di dalam manuskrip yang digubah di bawah lindungan Pangeran Arya Carbon dari Cirebon yang selesai ditulis pada tahun 1720, tokoh Prabu Siliwangi disebutkan sebagai raja Sunda yang beribukota di Pakuan-Pajajaran. Informasi yang sama juga didapatkan pada banyak manuskrip yang berasal dari pertengahan abad ke-19. Lantas apakah realitas pada teks yang menghubungkan Prabu Siliwangi dengan salah seorang raja Sunda adalah realitas historis?
Seorang ahli epigrafi, Hasan Djafar, menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi hampir tidak pernah disebutkan di dalam sumber-sumber primer, yang berasal dari prasasti dan naskah Sunda Kuna yang muatannya dapat dipercaya. Dari sekitar 23 prasasti dari masa kerajaan Sunda yang sudah diteliti, 11 prasasti di antaranya menyebut nama raja-raja Sunda, akan tetapi tidak ada satu pun yang menyebut nama Prabu Siliwangi. Hal tersebut bisa saja dipahami karena, Prabu Siliwangi bukan nama seorang raja dan nama gelar seorang raja, akan tetapi hanya sebuah julukan bagi salah satu di antara deretan raja-raja Sunda.Sumber dari karya sastra biasanya memang menyelaraskan Prabu Siliwangi sebagai raja Pajajaran. Akan tetapi kaitan Sang Prabu dengan kerajaan Pajajaran ditolak oleh seorang etnolog asal Belanda bernama CM Pleyte. Pleyte mengajukan sebuah pandangan bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah menjadi penguasa Pajajaran. Namun Prabu Siliwangi sama halnya dengan Prabu Wangi dari Carita Parahiyangan, yang telah tewas di tanah lapang Bubat. Prabu Siliwangi lebih identik dengan Prabu Wangi atau Prabu Maharaja dari kerajaan Sunda.
Setidaknya terdapat dua arus besar pandangan dari para ahli Sunda mengenai identifikasi Prabu Siliwangi. Pandangan yang pertama dilontarkan oleh seorang arkeolog Universitas Indonesia, Ayatrohaedi, yang mengidentifikasi Prabu Siliwangi dengan tokoh Raja Sunda bernama Niskala Wastukancana. Ayatrohaedi berpandangan bahwa Siliwangi berasal dari kata “silih” yang berarti “ganti”, dan “wangi” yang berarti “harum”; atau bermakna menggantikan seseorang yang harum atau tersohor namanya.
Raja yang harum dan tersohor namanya, bagi Ayatrohaedi, merupakan Prabu Maharaja yang gugur di tanah lapang Bubat. Sekalipun tahta kerajaan sementara sempat dipegang oleh Buni Sora selama enam tahun, Ayatrohaedi memandang Niskala Wastu Kancana merupakan raja pengganti Prabu Maharaja yang berjasa besar membangun kerajaan Sunda. Masa bertahtanya pun cukup lama, 104 tahun (1371-1475), hingga mangkat di Nusalarang. Jejak jasanya sebagai raja Sunda terekam di dalam beberapa prasasti. Pada prasasti Kawali IA, dari wilayah Astana Gede, Kawali, Ciamis, yang berasal dari abad ke-15, menyebut Niskala Wastu Kancana sebagai Prebu Raja Wastu yang bertahta di ibukota Kawali. Dialah yang memperindah kadaton Surawisesa, membuat parit yang mengelilingi ibukota, memberikan kemakmuran bagi seluruh desa, dan melaksanakan kebajikan agar lama jayanya di dunia. Namanya juga disebutkan di dalam Prasasti Kabantenan I (abad ke-16) dan Batu Tulis, Bogor (1533 M).
Justru pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Amir Sutaarga dalam "Prabu Siliwangi", serta Saleh Danasasmita dalam "Tokoh Prabu Siliwangi dalam Perspektif Sejarah". Kedua ahli tersebut justru mengidentifikasi Prabu Siliwangi sebagai Sri Baduga Maharaja, cucu dari Niskala Wastu Kencana, yang bertahta pada tahun 1482-1521, serta memindahkan pusat kekuasaan ibukotanya di Pakuan-Pajajaran. Pada masanya kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaan. Sri Baduga Maharja membangun kembali dan memperindah ibukota Pakuan, memariti sekeliling ibukota Pakuan, membuat monumen berupa gugunungan, membuat jalan yang diperkeras dengan batu (ngabalay), membuat hutan lindung (samida), dan membuat Talaga Warena Mahawijaya. “Tidaklah mengherankan bahwa Prabu Siliwangi atau SriBaduga Maharaja sampai dua kali mengalami pemberkatan (diwastu) dan masa pemerintahannya merupakan masa kejayaan dan kemakmuran,”
Terkait perbedaan pendapat tersebut, kemunculan sosok Prabu Siliwangi dapat dibaca sebagai sebuah fenomena zaman, gejala peralihan antara tatanan lama dan tatanan baru. Menurut Hasan Djafar, fenomena tersebut mirip dengan sosok Brawijaya yang dalam Babad Tanah Jawi disebut sebagai raja Majapahit akhir sebelum ditundukkan Demak.
“Prabu Siliwangi di wilayah barat Jawa, dan Brawijaya di wilayah timur Jawa, menjadi tapal batas antara tatanan lama dan baru, Kedua sosok itu merupakan gejala peralihan kepercayaan, agama, dan masa kejayaan,” ujar Hasan Djafar
Penulis : lham Aulia Japra